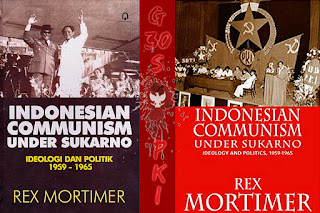Sekelompok pasukan berseragam Cakrabirawa, pengawal pribadi Presiden, melakukan semua itu. Waktu itu tak jelas atas perintah siapa. Hanya ada sebuah grup yang menyebut diri “Gerakan 30 September”.
Hari itu, beberapa belas jam lamanya orang bingung. Indonesia belum pernah mengalami kekerasan sedemikian mengguncangkan; tanpa peperangan, sejumlah perwira tinggi sekaligus tewas dalam semalam.
Presiden Soekarno, DN Aidit (kanan atas) dan Letkol Untung (kanan bawah).
Orang, terutama kalangan militer, kemudian menyebut kekerasaan itu “coup d’état”. Tapi itu sebuah distorsi. Coup l’état tak terjadi karena tak jelas posisi l’état (negara, atau pemerintahan) saat itu. Sejak 1958, sejak parlemen pilihan rakyat dibubarkan dan Bung Karno jadi Paduka-Yang-Mulia-Pemimpin-Besar-Revolusi-Presiden-Seumur-Hidup, praktis negara adalah dia, meskipun ia tak pernah memaklumkan, “l’état c’est moi”.
Tapi di awal Oktober 1965, Bung Karno tak bersuara, tak terlihat, sampai sekian jam, ketika seluruh Indonesia menunggu arahannya.
Tak berarti hari itu negara hanya cangkang. Bung Karno absen, tapi bayangannya masih kuat. Tentara terpecah, tapi tak berantakan. “Gerakan 30 September” tak jelas apa dan siapanya, tapi statemennya mengesankan adanya otoritas yang percaya diri. Bahasa yang mereka pakai menunjukkan kedekatannya dengan PKI, partai yang punya 3,5 juta anggota dan didukung pelbagai organisasi yang —menurut Ketua PKI D.N. Aidit di koran partai Harian Rakjat, 20 Agustus 1965— berkekuatan 27 juta.
Ketika militer, di bawah komando May. Jend Suharto, melumpuhkan “G30S”, PKI juga diam. Tak ada mobilisasi massa, tak ada pemogokan umum, apalagi sabotase dan perlawnan bersenjata.
“Setelah 30 September, sampai beberapa hari kami bekerja terus dengan normal, tapi tak seorang pun yang berhubungan dengan kami bisa memberi tahu apa yang terjadi atau apa yang harus kami kerjakan .... Ketika suasana Jakarta memburuk, kami hanya duduk di rumah menunggu instruksi. Suami saya tak diberi petunjuk apa yang mesti dilakukan dalam keadaan semacam itu. Kami tak memperkirakan keadaan akan berubah jadi begitu buruk. Kami pikir, memang Partai terdesak mundur, tapi akhirnya Bung Karno akan membereskannya.
Itu sebabnya dengan cepat Partai runtuh. Tak ada perintah, dan tak seorang pun tahu kemana harus berpaling atau siapa yang bisa dipercaya, sebab penahanan mulai berlangsung dan pengkhianatan terjadi .... Para pemimpin Partai mengirim pesan agar kami menunggu, dan saya tahu seorang isteri pemimpin Partai dikirim untuk menemui Bung Karno ....”
Tak lama kemudian, setelah ada orang-orang Partai yang berkhianat, sejumlah pemimpin PKI mengecam Ketua mereka. Aidit disalahkan dari kiri kanan.
DN Aidit sedang berbincang dengan Pemimpin China, Mao Zhedong.
Buku Mortimer menguraikan “otokritik” itu dengan mendalam. Saya coba mengikhtisarkannya: Aidit dianggap salah bersekongkol dengan sebuah gerakan yang setengah matang. Tentara pendukung “G30S” yang ditugasi menculik para jenderal tak berhasil mengangkut Nasution, musuh mereka yang paling berbahaya. Juga mereka salah langkah, membunuh jenderal-jenderal yang diculik. Tentara pasti akan dengan ganas membalas dendam hingga bahkan Bung Karno sekalipun akan sulit bernegosiasi untuk mencapai sebuah “penyelesaian politik”. Padahal suka atau tak suka, penyelesaian politik satu-satunya jalan. Gerakan tak akan mampu melawan pasukan Angkatan Darat yang bersenjata lengkap, berjumlah lebih besar dan dipimpin perwira-perwira yang berpengalaman.
Tapi salah Aidit lebih dalam: ia tak mempersiapkan PKI untuk sebuah antagonisme bersenjata. Ia terlalu jinak dengan Sukarno. Ia nampaknya tak yakin bahwa, seperti kata Mao Zhedong, “kekuasaan lahir dari laras bedil”. Bagi Aidit —tentunya dengan membayangkan Bung Karno—negara bukan sebuah kekuasaan yang harus dihancurkan dengan bedil. Negara punya dua aspek, kata Aidit: satu aspek pro-rakyat, aspek lain anti-rakyat. PKI harus memperkuat yang pertama dan mengalahkan yang kedua —meskipun tak dirinci bagaimana caranya.
Njoto (kanan berkacamata) sedang berbicara dengan DN Aidit (kiri).
Bagi pengecamnya, pandangan Aidit menyeleweng dari Marxisme-Leninisme: ia tak melihat Republik Indonesia sebagai negara borjuis yang harus dihadapi dengan perjuangan kelas.
Tapi adakah jalan lain? Orang-orang PKI yang anti-Aidit tak menawarkan apa-apa. Mereka tak melihat jangan-jangan “G30S” jalan lain itu: bukan revolusi, bukan kudeta, entah apa, tapi hendak melumpuhkan bagian negara yang anti-rakyat.
Aidit gagal, tapi kita tahu: memang muskil kekuasaan dicapai dengan asumsi bahwa partai komunis bisa berkuasa di negeri yang, dalam kata-kata Njoto, teoritikus PKI yang cemerlang itu, sebuah “lautan borjuis kecil”.
Goenawan Mohamad
Jurnalis Senior dan Pendiri TEMPO
18 Oktober 2021
www.facebook.com/gmgmofficial