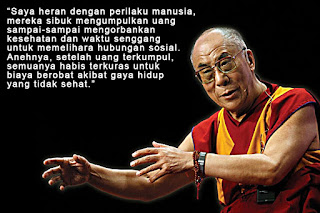Foto pertama adalah generasi “ponsel pintar” yang lahir pasca 1980-an dan direkrut perusahaan setelah 2006. Foto kedua adalah kumpulan para senior yang direkrut jauh sebelum krisis moneter 1997. Sebut saja generasi telepon. Ya, teleponnya telepon rumah, just a telephone. Atau kadang juga disebut generasi komputer, atau Gen X. Lahir setelah tahun 1960-an. Generasi ponsel pintar saat diminta bergaya bebas terlihat sangat ekspresif, lepas, riang, dan benar-benar bergaya bebas dengan gerakan tangan, mulut, dan badan yang “merdeka”.
Sebaliknya, saat diminta bergaya bebas, generasi telepon ternyata benar-benar jadul. Kaku, tidak ekspresif, dengan gerakan tangan yang terbatas. Paling-paling cuma sekadar angkat jempol. Entah karena umur, agak jaim, atau memang sejak sekolah dibelenggu banyak aturan yang menyebabkan mereka menjadi generasi pasif yang menunggu, tak banyak pilihan dan menghadapi banyak risiko.
Beda benar dengan generasi ponsel pintar yang dibesarkan dalam iklim demokrasi yang lepas, banyak pilihan, penuh keberanian, dan kebebasan. Lantas, apa hubungannya antara gaya berfoto dan produktivitas kerja? Benarkah beda generasi telah menjadi sebuah masalah bagi bangsa ini?
Saya pernah menulis adanya empat generasi yang menjelaskan mengapa kurikulum baru disambut dengan berbagai pandangan. Adalah keyakinan saya, jurang antargenerasi tak dipahami para pemikir pendidikan. Keempat generasi itu adalah generasi kertas-pensil (lahir sebelum 1960), generasi telepon/komputer (lahir 1960–1970), generasi internet (lahir 1970–1980), dan generasi ponsel pintar (lahir setelah 1980).
Tentu saja selain masalah beda generasi, kita juga membedakan mana pandangan orang yang mengerti masalah, yang senang melihat masalah, dan mana yang ingin mengatasi masalah. Sebuah gap yang dulu terjadi tanpa perbedaan yang jelas, sekarang justru menjadi masalah besar. Anda mungkin masih ingat, ketika apa yang dimainkan di rumah sama dengan yang dimainkan di sekolah.
Misalnya saja mobil-mobilan dari kulit jeruk bali, juga menjadi mainan di sekolah. Anak-anak perempuan bermain boneka dengan Dakocan yang kulitnya hitam gelap atau boneka Barbie di rumah, juga di sekolah. Masa emas itu kini telah berlalu. Apa yang mereka mainkan di rumah (video dan electronic games) kini tak boleh lagi dibawa ke sekolah. Oleh generasi kertas-pensil dan generasi telepon, video game dianggap kurang mendidik. Jangankan video game, kalkulator saja adalah pembodohan, sedangkan sekolah internasional yang berbahasa Inggris dinilai melanggar Sumpah Pemuda.
Tanahnya sudah dikorek habis. Bagi generasi ponsel pintar, Indonesia adalah negeri dengan jumlah orang kaya yang fantastis. Alamnya miskin, tetapi orangnya kaya-kaya. Jadilah generasi yang bingung: diberi subsidi negara tetapi malah dipakai buat foya-foya, sedangkan yang dari swasta, kalau semakin mahal, semakin diburu. Tak bisa sekolah internasional di sini, ya pindah ke luar negeri.
Guru bilang A, murid melakukan B. Sekolah mengutamakan angka nilai dan otak kiri, tetapi mereka mengembangkan keterampilan lapangan dan otak kanan. Gap ini bukanlah ilusi. Tetapi terjadi sungguhan. Seperti Anda ketika ditanya orang tua “apa cita-cita mu kelak ke depan, Nak?” Maka jawabannya adalah nama-nama fakultas seperti dokter, ekonomi, psikologi, lawyer, sastrawan, atau seniman.
Semuanya ada fakultasnya. Tetapi bila hal serupa Anda tanyakan pada anak-anak sekarang, Anda akan terbengong-bengong sebab mayoritas keinginan mereka tidak atau belum ada nama fakultasnya di sini. Ada yang mau jadi sutradara film, fashion desainer, pelukis, fotografer, perancang pesawat terbang, pembuat robot ruang angkasa, atau bahkan juru masak, social entrepreneur, atau artpreneur.
Basuki Cahaya Purnama alias Ahok bersama isteri dan 3 anaknya.
Kegelisahan Ahok
Ahok, wakil gubernur DKI, bukanlah generasi kertas. Dia dilahirkan pada tahun 1966. Jadi ketika dewasa, dia merasakan nikmatnya komputer, lalu memakai internet belakangan. Namun, Ahok gamang saat melihat pegawai-pegawainya yang masih muda (mungkin generasi ponsel pintar) justru membuat notulensi dengan pensil (bolpoin) dan kertas, bukan langsung menulis di laptop.
Ahok pantas berang, sebab setiap tahun pegawai-pegawai itu mengajukan permintaan anggaran untuk membeli laptop. Laptop di depan meja, tetapi tulisnya tetap saja di kertas. Ini benar-benar pemborosan. Namun, para eksekutif yang menjadi mentor untuk menjembatani generation gap mengajukan usul lebih jauh dari Ahok. “Jangan suruh orang lain menjadi notulis. Kita saja, pemimpin, harus bisa langsung menulis report di depan mata, di komputer, yang langsung bisa di-share melalui internal media,” inilah yang disampaikan sejumlah eksekutif. Memang ini merepotkan.
Bagi saya saja repot, apalagi bagi kita yang sudah biasa dilayani. Kegelisahan Ahok seharusnya tidak boleh sekadar menjadi tontonan di YouTube atau TV saja, melainkan juga sinyal bagi kita semua. Apa yang dialami Ahok adalah realita generation gap yang diakibatkan pembekuan yang dilakukan hampir semua lembaga dan badan pemerintah di era krisis moneter. Bukan main, 7–8 tahun freezing merekrut pegawai antara 1997–2006, bahkan beberapa lembaga birokrasi melakukan zero growth berkali-kali.
Grup band SLANK menyebut dirinya "Generasi Biru".
Di banyak perusahaan, bahkan bukan cuma freezing, melainkan juga PHK. Maklum, SDM ada dalam komponen biaya. Apa akibatnya? Kumpulan orang tua menguasai lembaga. Kalau saya lihat, pegawai yang dimarahi Ahok itu rasanya dari wajahnya berkisar masuk pada Generasi Ponsel Pintar. Tetapi mengapa ia tak memakai laptop langsung? Pengalaman saya menemukan, dalam konteks generation gap, kaum muda yang dinamis akan menjadi sama dengan seniornya, terbelenggu dan tak ada bimbingan untuk menegakkan aura generasinya yang memberikan kekuatan kreativitas dan teknologi yang besar.
Jadi, generasi muda di banyak lembaga dan dunia usaha kita porsinya sudah tinggal sedikit, sedangkan generasi tua begitu banyak. Sudah banyak, mereka menguasai pangkat teratas. Itulah yang disebut band Slank sebagai feodalisme. Salah satu bait lirik lagu itu berbunyi begini:
“Salah nggak salah, sama atasan slalu diturutin
Maunya seumur hidup minta-minta dihormatin ….
Benar nggak benar yang lebih tua sudah pasti benar
Suruh-menyuruh, larang-melarang dia-dia yang paling benar ….”
Jadi, sekarang jelas mengapa reformasi birokrasi susah, biaya perjalanan dinas terus membengkak kendati peningkatan kesejahteraan PNS tidak terjadi, atau kendati rapat pakai BB Group, Skype, Kakao, atau pakai Line saja sudah cukup.
Sedangkan para manajer dari negara yang tak terbelenggu feodalisme, selain atasan berani turun langsung ke bawah, bahkan melakukan wawancara di bursa-bursa tenaga kerja, mereka juga memutuskan dengan cepat sendiri ke bawah. Kala feodalisme merajalela, atasanlah sasaran pelayanan, mereka sulit turun ke bawah. Dan, pantaslah produktivitas terganggu. Potensi besar generasi baru itu perlu didampingi mentor-mentor hebat, karena mereka punya kekuatan menembus batas yang mengalahkan kekuatan generasi di atasnya.
Mereka kini disebut juga sebagai generasi VUCA, yang dibesarkan dalam lingkungan yang Volatile, Uncertain, Complex, dan Ambiguous. Artinya, mereka generasi tahan banting dan adaptif ditempa dalam pergulatan yang cair dan tidak pasti, tapi punya kemembalan, daya penetrasi yang kuat dan lincah bergerak. Jadi, bagaimana sistem pendidikan yang dikomentari kaum tua yang kolot yang masih berpikir hanya dirinya yang benar? Bagaimana reformasi birokrasi?
Bagaimana meremajakan partai-partai politik dan sekaligus meluruskan makna subsidi dan sosial? Semua hanya bisa dilakukan kalau jembatan antara generasi segera dibangun.Yang tua sadar untuk memberi ruang bagi kaum muda untuk maju, yang muda tetap respek, tapi yang jelas negeri ini butuh manusia yang kaya perspektif. Bukan orang yang merasa paling benar, padahal ada kacamata kuda di wajahnya.
Rhenald Kasali
Ketua Program MM UI
Koran SINDO, 14 Februari 2013